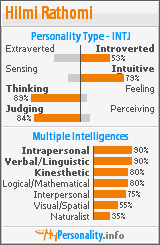Pemberdayaan Komunitas Terintegrasi
by: Hilmi Sulaiman Rathomi, MD
Rasionalisasi:
Penatalaksanaan masalah sosial di masyarakat harus dilakukan secara holistik, ekliktik, dan komprehensif. Setiap individu harus dijamin dapat memenuhi kebutuhan hidup primer dan memiliki akses kebutuhan dasar, dan jaminan tersebut harus terintegrasi. Antara satu jaminan/fasilitas saling menjadi syarat bagi jaminan yang lain dan saling terkait.
Mobilitas vertikal lintas generasi hukumnya wajib. Karena itu, lingkaran setan mata rantai kemiskinan harus diputus. “Orang tua boleh supir angkot, tapi anaknya minimal mesti jadi pilot”
Tujuan Program:
Pemberdayaan komunitas kurang mampu secara terintegrasi. Hasil akhir yang diharapkan adalah komunitas sejahtera, yang minimal mampu memenuhi kebutuhan primer (sandang, pangan, papan) dan memiliki akses kebutuhan hidup dasar (kesehatan dan pendidikan).
Komponen Program:
• Education Empowerment
• Health Empowerment
• Economic Empowerment
• Social Empowerment
Fasilitas dan Persyaratan:
1. EduPower
Fasilitas: Mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), wajib belajar (WAJAR) 12 tahun
Syarat:
- Imunisasi anak lengkap
- Orangtua bekerja
- Keluarga melakukan general checkup sesuai jadwal
2. HealthPower
Fasilitas: Mendapat imunisasi dasar lengkap, general checkup berkala, asuransi kesehatan
Syarat:
- Anak mengikuti PAUD dan WAJAR
- Orang tua bekerja
3. EcoPower
Fasilitas: Memiliki pekerjaan
Syarat:
- Anak mengikuti PAUD dan WAJAR
- Imunisasi anak lengkap
- Keluarga melakukan general checkup sesuai jadwal
4. SocialPower
Fasilitas: Mendapatkan rumah/tempat tinggal yang sehat dan layak huni
Syarat:
- Orang tua bekerja
- Anak mengikuti PAUD dan WAJAR
- Imunisasi anak lengkap
- Keluarga melakukan general checkup sesuai jadwal
Algoritma Program:
• Pemilihan kawasan binaan (RT/RW)>>pengumpulan data kependudukan/pemetaan penduduk>>klasifikasikan menjadi 2: mampu dan kurang mampu
• Penduduk kurang mampu>>informed consent program>>mulai dengan pemberian imunisasi dasar pada anak, PAUD, dan Sekolah (sesuai usia anak masing2)>>evaluasi selama 3 bulan
• Selama 3 bulan, para orang tua diberikan pelatihan ketrampilan kerja sesuai bidang yang akan ditekuni masing2
• Jika hasil evaluasi setelah 3 bulan:
o Baik>>berikan pekerjaan kepada orang tua>>evaluasi imunisasi, PAUD, sekolah (pada anak), dan performa pekerjaan (orang tua)>>evaluasi 3 bulan>>jika hasil baik>>berikan perumahan layak huni dan sehat>>evaluasi dalam 3 bulan>>berikan jaminan kesehatan>>evaluasi secara berkala
o Buruk>>intervensi orang tua>>jika berhasil, mulai program dari awal>>jika gagal>>sanksi sosial untuk orang tua>>anak dipindah, diberikan orang tua asuh
Keterangan:
1. Orang tua bertanggung jawab sepenuhnya pada anak masing2. Ketika anak tidak sekolah, tidak imunisasi, atau melakukan kewajiban lain, maka sanksi akan dikenakan pada orang tua
2. Semua fasilitas yang diberikan adalah saling terkait, dan semua persyaratan harus dipenuhi. Jadi, untuk mendapatkan rumah sehat dan jaminan kesehatan (indikator kesejahteraan), orang tua harus bekerja, dan untuk bekerja, orang tua harus memastikan bahwa anak mengikuti sekolah, dan agar anak boleh mengikuti sekolah, anak harus dipastikan telah mendapat imunisasi dasar lengkap.
Special Issue: EcoPower
• Seperti kata pepatah, “Lebih baik memberi kail daripada seekor ikan”.
• Pendekatan pemberdayaan ekonomi, tidak bisa hanya sekedar memberi kail, tapi harus integratif, sesuai kontinuumnya.
• Kira2 seperti ini: Berikan ikan untuk sementara (simtomatik)>>ajari cara memancing>>berikan kail>>sediakan kolam/sungai/tunjukkan tempat yang banyak ikannya>>sediakan pasar untuk menjual ikan hasil pancingan (karena pasti akan sangat membosankan jika tiap hari hanya makan ikan)>>pastikan ada orang yang membeli ikan hasil pancingan
• Setelah memiliki ketrampilan kerja, masyarakat harus diberikan pekerjaan/tempat usaha. Untuk memiliki tempat usaha yang baik, harus terjalin kerjasama dengan pengelola pasar/pusat perbelanjaan. Sebagai kontrapretasi, perusahaan/pemberi kerja/penyedia tempat usaha bisa mendapatkan produk dengan harga murah.
• Agar ada konsumen yang membeli produk, harus diberikan kontrapretasi. Misal, produk karya komunitas tersebut dijual di satu toko semacam toko serba ada, dan konsumennya dibuatkan sistem member. Tiap member secara otomatis akan mendapatkan asuransi kesehatan, yang preminya adalah dengan membeli produk hasil kerja dari komunitas tadi.
Investasi:
• Biaya penyelenggaraan PAUD
• Beasiswa wajib belajar 12 tahun
• Biaya pelatihan ketrampilan kerja
• Pembuatan Rumah Sehat Layak Huni
Kerjasama:
• CSR Korporat bidang Industri >> feedback untuk perusahaan dapat berupa produk komunitas dengan harga murah, dll.
• CSR Korporat bidang Developer/kontraktor
Target:
• Dalam waktu 1 tahun, komunitas binaan telah mampu mandiri, sehingga tinggal dilakukan monitoring dan evaluasi program, dan bisa mencoba ekspansi ke komunitas target berikutnya.