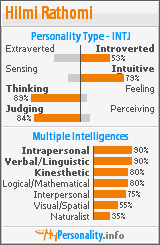Idealisme adalah salah satu kata paling mewah yang ada dalam kamus kehidupan. Tidak semua orang mampu memilikinya, dan diantara yang memilikinya pun, belum tentu semuanya menempatkannya pada posisi yang benar. Tidak sedikit orang yang memiliki idealisme yang kemudian mendudukkannya hanya sampai pada level pengetahuan, belum pada taraf sikap, apalagi mencapai tingkatan perilaku. Sedang orang-orang yang tidak memilikinya, sibuk berlindung dibalik alasan bahwa merasa tidak pantas, atau justru tidak butuh. Mungkin tadinya punya, tapi lantas dibuang.
Kita membutuhkan idealisme untuk mengisi kehidupan. Pada setiap profesi, apapun itu, pasti ada idealisme yang diperjuangkan dan menjadi latar belakang kemunculan profesi tersebut. Dalam kurikulum pendidikan doktoral –tingkatan keilmuan tertinggi yang mampu didefinisikan manusia modern- selalu disertakan mata kuliah filsafat ilmu. Semua calon doktor diwajibkan untuk mengakrabi pernik idealisme dalam bidang keilmuan masing-masing; mulai dari asal-usulnya, bagaimana ilmu tersebut diperoleh, bagaimana ilmu dikembangkan, dan seterusnya. Hal inilah yang kemudian menjadi pembeda absolut antara para doktor dengan sekedar sarjana. Seorang doktor dituntut untuk menjadi kaum terpelajar sejati, ilmuwan tulen yang mampu mewarnai perkembangan ilmu pengetahuan dan mengisi kehidupan. Tidak seperti para sarjana yang seringkali hanya merupakan ilmuwan tanggung, yang –kebanyakan- hanya didesain untuk menjadi kumpulan tukang, ahli teknis di bidang masing-masing demi menyambung kehidupan, karena tidak semua dikenalkan dengan idealisme profesinya.
Dalam menjalankan profesi apapun, ketika kehilangan idealisme, maka yang kita lakukan hanyalah menyambung hidup, bukan mengisi kehidupan. Kita hanya mencari penghidupan dari keahlian yang kebetulan kita kuasai, dan orang lain tidak. Kasarnya, kita mencari duit dari kelemahan orang lain. Dimana ada kelemahan, ada kebutuhan untuk dibantu, disitulah tambang uang. Jika sudah begitu, maka hanya tipis bedanya antara guru, penulis, pelukis, dokter, pengacara, atau ustadz, dengan para pelacur. Masing-masing menjual asset yang dimilikinya untuk, -sekali lagi- sekedar menyambung hidup. Para guru dan dosen menjual ilmunya, para penulis menjual keahliannya merangkai kata, para pelukis menjual keterampilannya mengkombinasikan warna, para dokter menjual kepandaiannya dalam bidang pengobatan, para pengacara menjual ilmu hukumnya, para ustadz menjual pengetahuan agamanya, dan para pelacur menjual kelaminnya. Semuanya untuk uang, demi dapat menyambung kehidupan masing-masing.
Sebagaimana kita tahu, pusat peredaran uang adalah di pasar. Maka, jika ingin terlibat dalam lingkaran peredaran uang, kita terpaksa harus takluk pada kemauan pasar. Apapun profesi kita, selera pasar harus menjadi prioritas. Jika kita guru, kita hanya akan meneruskan kebiasaan, mengajarkan ilmu yang melestarikan kekuasaan para penguasa, alih-alih memberikan pendidikan yang membebaskan&mencerdaskan. Jika kita dokter, maka kita akan senang jika pasien datang berobat dalam jumlah berjubel, diresepkan obat, tanpa disertai pemberian pengetahuan bagaimana seharusnya mereka menjaga kesehatan secara mandiri. Atau jika kita ustadz, kita akan dengan senang hati jika diminta memberikan nasihat yang berisi ajakan untuk selalu berbuat baik, tapi enggan ketika diminta melarang ini dan itu. Karena larangan, nahi munkar, bukanlah bagian dari selera pasar.
Bagi orang-orang yang memiliki idealisme dalam kerangka yang benar, pasar akan ditempatkan pada posisi yang selayaknya, tidak terlalu tinggi dan tidak kelewat rendah. Bukan melulu diposisikan sebagai seorang tuan yang harus diikuti kemauannya, dan bukan pula sebagai pihak yang harus dipaksakan menuruti selera pribadi kita, yang juga belum tentu benar arahnya. Terus-menerus merelakan diri mengikuti kemauan pasar adalah serupa dengan melacur. Sedangkan ngotot memaksakan idealisme pribadi tanpa kompromi adalah seperti kastrasi.
Jangan terlalu murah dalam mematok harga idealisme, prinsip, ataupun nilai yang kita yakini benar. JIka kita tidak ingin dianggap sebagai para pelacur kehidupan, silakan perjuangkan idealisme kita masing-masing. Jangan sekedar menjual asset atau bercita-cita menjadi sesuatu hanya demi beberapa lembar rupiah. Jadilah guru yang mencerdaskan, musisi yang tidak selalu ikut arus, penulis yang tidak selalu mengekor kemauan para pemodal media, produser film yang tidak melulu ikut-ikutan tren, dokter yang tidak hanya memperjuangkan kesembuhan tapi juga kesehatan, atau ustadz yang tidak hanya berani ber-amar ma’ruf tapi juga ber-nahi munkar. Janganlah sekedar berupaya untuk menyambung hidup, tapi berusahalah juga untuk mengisi kehidupan.
Wallahua’lam.