
Saya tidak sedang dalam posisi membela Pak SBY, atau justru berada di sisi yang sama dengan Prof.DR.George Junus Aditjondro. Bukan masalah isi buku “Membongkar Gurita Cikeas” yang menggoda saya untuk menulis, karena saya sendiri belum membaca buku tersebut. Toh, kalaupun saya sudah baca, saya tetap tidak punya wewenang ilmiah untuk mengomentari isi buku tersebut. Jika pun ada orang yang memaksa saya untuk mengomentari isi buku itu, tanggapan saya mungkin sama levelnya dengan komentar ala mas2 tukang becak, abang2 tukang ojek, atau mbak2 yang menunggu pelanggan di warung kopi.
Adalah statement Aditjondro yang akhirnya menstimulasi saya untuk menulis. Statement ini mengusik ingatan ketidaksukaan saya tentang fenomena perdebatan melalui buku. Dalam berbagai wawancara, Aditjondro menyatakan bahwa dirinya adalah Doktor, SBY juga Doktor. Maka, jika ingin mengcounter buku yang telah dirilisnya, silakan SBY menulis buku, selesaikan dengan cara ilmiah. Bukan dengan mencekal bukunya, atau justru membawa perkara ini merembet ke meja hijau, meskipun dirinya siap untuk itu.
Jika masalahnya hanya soal haramnya mencekal peredaran buku, itu tidak saya tolak. Pun usulan untuk jangan menyeret perkara ini ke pengadilan, saya setuju 100%. Presiden harus memberikan contoh bagi masyarakat untuk menyelesaikan masalah secara gentlemen. Secara, masyarakat kita sekarang ini semakin cemen dan norak. Kena pukul dikit, ngadu ke pengadilan. Diledekin secuprit, ngadu ke polisi. Dokter salah ngomong satu kata, lapor ke pengacara, dijadikan isu malpraktik. Apakah berarti masyarakat kita semakin sadar hukum? Menurut saya tidak. Itu namanya cemen, pengecut. Karena nggak berani menghadapi sendiri, ngomong sendiri, dan menyelesaikan secara kekeluargaan, jadi mesti bawa2 pengacara. Siapa yang untung? Pengacara lah.
Nah, kalau bukan masalah pencekalan atau pengadilan, berarti yang tidak saya setujui di sini adalah masalah buku dibalas buku. Makin ke belakang, fenomena ini makin marak. Banyak pihak yang saling menghujat lewat buku, berantem bersenjatakan buku. Mulai dari NU lawan Muhamadiyah, Oposisi lawan Pemerintah, agama X lawan agama Y, gerakan IM lawan gerakan S, dst. Yang untung siapa? Penerbit, pebisnis buku. Yang rugi? Masyarakat. Satu, karena tidak mendapatkan konklusi dari perdebatan tersebut. Dua, karena jika ingin mengikuti perdebatan tadi hingga tuntas, masyarakat harus merogoh kantong lebih dalam untuk membeli buku2 yang dirilis oleh masing2 pihak. Pengarangnya? Cuma mendapat kepuasan semu karena bukunya banyak beredar, tapi tidak memberikan banyak manfaat untuk masyarakat. Mereka mengidap salah satu komplikasi narsisme yang paling serius.
Perdebatan melalui buku –menurut saya- akan selamanya kontraproduktif, karena hanya akan menjadi wahana masturbasi intelektual para pengarangnya. Mereka itu tidak mencari kebenaran, tapi pembenaran. Bohong besar jika tujuannya untuk mencerdaskan masyarakat atau membuka mata rakyat. Karena kebenarannya belum tentu teruji, belum tentu telah ditelaah dari sudut pandang yang berimbang. Jika memang ingin mengungkap kebenaran untuk masyarakat, silakan buat forum, duduk bersama, lakukan perdebatan, baru bukukan kesimpulannya, dan pasarkan seluas-luasnya.
Saya terpaksa membawa perkara ini ke persoalan global warming, ke wilayah environment sustainability. Karena seperti yang kita tahu, kertas itu mahal bung! Harus dihemat, direduksi penggunaannya jika kita tidak ingin berkontribusi pada memburuknya iklim dunia. Kalaupun terpaksa menggunakan kertas, jadikanlah dia kumpulan kertas yang bermanfaat, jadikan dia buku2 yang berkualitas. Bukan buku2 yang saling hujat, yang dibuat untuk menuntaskan syahwat penulisnya, padahal belum jelas kebermanfaatannya. Dan bukan pula buku2 plagiat yang tidak berkualitas, yang asal jadi dan hanya dibuat demi melampiaskan narsisme sang pengarang. Saya pernah sangat sebal dengan hal ini. Dulu, saya pernah melakukan kesalahan, tertipu karena membeli buku yang kurang bermutu, 2 kali, macam keledai. Pasalnya, buku yang bersangkutan dicetak ulang dengan judul yang berbeda, cover yang berbeda, oleh penerbit yang berbeda, dan semua buku di toko tersebut masih berplastik rapat. Ternyata, itu buku yang sama yang dulu pernah saya beli, dan jelek. Hhh....
Nah, bagi yang suka menulis, silakan menulis. Tapi tolong, jangan habiskan hutan Indonesia hanya untuk melampiaskan nafsu Anda yang ingin populer, famous, dikenal orang karena telah menulis buku ini dan itu. Bikinlah buku yang bagus, punya nilai tambah, bermanfaat, dan sesuai keahlian masing2. Bagi para penerbit, mbok ya lebih diseleksi karya2 yang masuk. Sekarang ini, untuk jadi penulis buku udah kelewat gampang. Tapi buku yang dirilis juga nggak sedikit yang kelewat nggak mutu. Tolong jangan cuma pertimbangangkan kepentingan bisnisnya, tapi juga manfaatnya buat orang banyak. Dan satu lagi, buat para pengacara, mbok ya jangan kayak orang kurang kerjaan, kurang duit. Semua dipanas2in untuk ke pengadilan. Toh, kami, para dokter juga sedang menggeser paradigma, dari sakit menjadi sehat. Kita sudah tidak lagi berharap banyak pasien, banyak orang sakit, tapi berusaha menjaga masyarakat tetap sehat. Kalian juga lah, silakan edukasi masyarakat, mana perkara yang bisa diselesaikan secara kekeluargaan, mana yang memang mesti menempuh prosedur hukum. Masalah rejeki mah, udah ada yang menjamin. Asal jangan bergantung pada manusia, tapi bergantunglah pada yang menciptakan manusia.
Wallahua’lam.

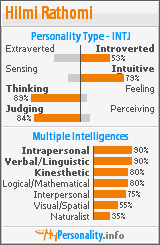

Tidak ada komentar:
Posting Komentar