
Saya punya perbekalan alasan yang lebih dari cukup untuk akhirnya memutuskan menulis menjelang hari Ibu. Tidak ada niatan saya untuk latah, atau mengekor jutaan penulis lain yang pasti tidak ingin melewatkan momen ini begitu saja. Biasanya, mendekati hari Ibu seperti sekarang ini, hari-hari kita akan dipadati blog2 puitis dan kolom2 melankolis yang akan mengajak kita berkontemplasi betapa kita tak akan mampu membalas lunas cinta seorang ibu. Bahkan sebelum kita berhasil menamatkan satu tulisan saja, tanpa sadar air mata kita telah berhamburan, berebutan untuk keluar melalui sudut2 yang ada. Mata kita mendanau, sebuah telaga kecil telah tercipta dengan sempurna diantara kelopaknya. Air mata itu seperti mengiyakan pepatah bahwa kasih seorang Ibu memang akan sepanjang masa. Dia (air mata itu) seakan hadir untuk menyempurnakan ucapan terimakasih kita untuk Ibu kita, karena diksi seringkali gagal mewakili suara hati secara presisi.
Bukan keahlian saya untuk memerah air mata manusia. Suatu kali pernah saya coba paksakan, tapi akibatnya justru serupa dengan usaha bunuh diri. Belum sempat saya tuntaskan itu tulisan, eh, air mata saya sudah berloncatan tidak karuan. Gagal total.
Beberapa hari lalu saya terpaksa membaca ulang Bumi Manusianya Pramoedya, dan Para Priyayinya Umar Kayam. Terpaksa memang, karena tidak direncanakan. Kebetulan ada seorang teman yang baru saja membaca, dan langsung jatuh cinta –katanya-. Saya punya ingatan yang telanjang bahwa buku2 Pram (dan Umar Kayam) memang meninggalkan kesan yang mendalam ketika saya khatamkan dahulu. Tapi ingatan tentang bagian mananya yang impresif, itu yang dibawa kabur oleh waktu, dicurinya dari gudang memori saya. Mungkin saat itu saya sedang tidak ada di rumah.hehe.Yah, terpaksa harus saya rebut kembali. Saya baca ulang.
Saya tidak ingin membahas tentang betapa perlawanan terhadap feodalisme dibahas dengan brilian di kedua buku itu. Concern saya saat ini, justru tentang para wanita di buku-buku itu, para Ibu yang berhasil lulus casting ala Pram dan Umar Kayam, sehingga ikut diabadikan dalam buku2 mereka.
Keprihatinan saya yang paling dalam seketika muncul ketika mengetahui bahwa ada orang yang mencuri –maaf- celana dalam wanita, divonis harus mendekam di penjara selama 5 tahun. Ada pula buruh yang mencuri 2 kilogram kapas senilai 4 ribu rupiah, mesti dikurung sembari menunggu putusan sidang. Mengapa mereka dihukum? Karena mereka mengaku, pikir saya. Sementara itu, ada orang lain, yang bukan buruh, bukan fakir, bukan miskin, dan tidak sedang kelaparan, mencuri uang milik rakyat bernilai trilyunan. Mungkin kalau uang itu kalau dibelikan kapas bisa dapat berton-ton, atau bisa juga untuk membeli celana dalam yang bisa dipakai oleh seluruh rakyat Indonesia. Dipenjarakah mereka? Boro2. Bisa jadi saat ini mereka sedang dugem atau main golf menghabiskan uang haram itu. Ironisnya, mereka tidak mengaku. Mereka lebih suka berlakon ala bajaj, ngeles, dan menyumpal palu para penegak hukum dan menjejali dompet mereka dengan uang hasil curian juga. Dugaan terbaik saya, minimal ada dua hal yang berperan dalam mencetak mental busuk para pejabat kita. Satu, masalah keberkahan. Kedua, perkara peran keibuan.
Mungkin setengah berbau kebatinan, tapi saya sangat percaya dengan yang namanya berkah. Uang yang tidak halal, berapapun jumlahnya tidak akan cukup untuk membeli keberkahan Allah. Makanan yang tidak baik, didapatkan dari cara yang menjurus haram, sesedikit apapun, bisa mencerabut keberkahan Allah dari konsumennya. Orang yang hidupnya kehilangan keberkahan, jalan hidupnya akan sulit langgeng, dan bisa2 gagal mewujudkan misi untuk menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain.
Para oknum pejabat, orang-orang kaya, para Jendral, dan para pembesar lainnya yang sekarang sedang menjadi tirani di negeri ini –prediksi saya- mayoritas adalah anak para priyayi jaman kolonial. Mereka adalah keturunan yang lahir dari kaum yang mengais rejeki dari menggerogoti belulang bangsa sendiri demi kemuliaan diri dan keluarga. Mereka menciumi sandal para kompeni demi mendapatkan jabatan tinggi. Yah, meskipun ada pula golongan priyayi yang memang mulia, yang memahami bahwa meningkatnya kedudukan beriringan dengan meningkatnya tanggungjawab untuk membangkitkan bangsa. Wallahua’lam, na’udzubillahi min dzalik, mungkin dari sinilah keberkahan anak keturunan mereka mulai terkikis.
Nah, yang kedua, masalah peran keibuan. Jika kita membaca sejarah, atau membaca novel sejarah semacam Bumi Manusia dan Para Priyayi, kita akan mudah untuk menyimpulkan bahwa peran perempuan dalam masyarakat Indonesia dahulu sangat terkerdilkan. Bahkan pada kaum priyayi sekalipun. Perempuan telah didesain memiliki hak yang kelewat terbatas, lalu mereka terpaksa mempercayainya, dan kepercayaan itu diwariskan pada anak perempuan dalam keluarga.
Pada masa itu -menurut saya- perempuan hanya diplot sebagai istri, bukan dipersiapkan untuk menjadi Ibu. Jobdesc perempuan disimplifikasi, dan ranah aktivitasnya dikerangkeng sebatas dapur, sumur, dan kasur. Yang paling gawat, potensi utama seorang Ibu sebagai pendidik digunduli dan dipangkas habis. Perempuan jaman itu tidak terdidik, dan tidak disiapkan untuk jadi pendidik. Wajar jika anak-anaknya kemudian seperti tidak pernah mendapatkan sentuhan didikan ala seorang Ibu, yang lebih banyak ke perkara softskills. Produk generasi itu memiliki kualitas budi pekerti yang minimal, mental yang melempem, dosis kejujuran yang kelewat sedikit, keberanian yang tipis, pemahaman agama yang dangkal, dan seterusnya. Sekolah formal bisa jadi akan kesulitan mengajarkan penatalaksanaan semua masalah tadi, tapi sekolah ala Bunda di rumah saya yakin pasti bisa.
Perempuan itu kadang serupa dengan pers. Dahulu dikekang, sekarang bebas. Mungkin memang terinspirasi dari pers, ada juga perempuan yang oportunis dan bertingkah kelewat batas. Macam infotainment, semua perkara di muka bumi dianggap jadi hak mereka untuk disiarkan, ditonton dan didengar seluruh pasang mata-telinga manusia. Pokoknya bebas. Ironisnya, mereka yang mempertuhankan kebebasan itu, walaupun di satu sisi sukses merebut kembali hak-hak perempuan yang sempat tercerabut, di sisi lain kewajiban utamanya justru terbengkalai. Sunnahnya jalan, fardhunya kedodoran.
Perempuan itu, sebelum menjadi apapun profesinya, sejatinya ia adalah calon Ibu. Maka ia harus belajar dan dikondisikan untuk mendapatkan kurikulum pendidikan keibuan. Dari kecil, kebanyakan orang tua kita lebih banyak menanyakan tentang cita2, profesi, mau jadi apa kelak ketika besar, dan mengecek setiap hal yang berkaitan dengan cita2 tadi secara berkala. Sudah mengerjakan PR atau belum, sudah belajar atau belum, dan seterusnya. Tapi perkara lain yang lebih pasti, bahwa si gadis ini akan menjadi Ibu, jarang sekali dikonfirmasi kemajuannya. Apakah si anak ini sudah cukup memahami agama, menguasai ketrampilan manajemen keuangan rumah tangga, memasak berbagai makanan yang memenuhi kebutuhan gizi keluarga, hingga kemampuan mendidik anak. Sayang sekali.
Yasudahlah, itu masa yang sudah lewat. Durhaka rasanya kalo kita menyalahkan orang2 tua kita atas apa yang terjadi pada diri kita sekarang. Urusan kita adalah masa depan, bukan masa lalu. Dalam konteks peningkatan peran keibuan, yang bisa kita perbuat kini adalah hendaknya masing2 perempuan mempersiapkan diri untuk menguasai seluruh kompetensi wajib seorang Ibu. Para lelaki pun tidak bisa tak acuh, berpikir bahwa ini bukan porsinya. Karena bisa jadi anak kita nanti adalah perempuan, yang juga akan menjadi calon Ibu, yang otomatis harus terpapar dengan kurikulum pendidikan calon Ibu. Karena itu, pastikan calon anak kita nanti akan mendapat didikan yang baik, dari seorang Ibu terpilih, yang juga baik.
Jangan lagi mereproduksi generasi bermental tempe, yang bahkan untuk bertobat dan mengakui kesalahan diri sendiripun malu.
Selamat hari Ibu.
Selamat menjadi Ibu dan calon Ibu.
Doa saya untuk seluruh Ibu di seluruh dunia.

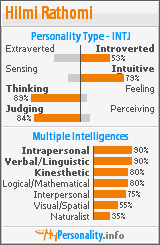

kak hilmi... aku boleh share postingan ini yaa... nuhun :)
BalasHapus