
Paling seimbang adalah alasan utama mengapa akhirnya saya memilih untuk menjadi dokter. Saya ingat, hingga detik-detik terakhir menjelang batas waktu pengumpulan formulir pendaftaran SPMB, pilihan menjadi dokter sama sekali tidak pernah terlintas dalam benak saya. Namun entah kenapa dalam pertapaan singkat yang saya lakukan, tiba-tiba, ting! Kata dokter tiba-tiba muncul, lengkap dengan bohlam yang menyala terang di sebelah kepala seperti di film-film kartun. Saya telpon orang rumah, lalu di-acc, dan saya pilih pendidikan dokter UI sebagai pilihan pertama saya.
Ketika saya kecil, jika orang bertanya tentang cita-cita, maka saya selalu menjawab dengan keyakinan penuh: Profesor! Dulu, saya tidak tahu bahwa profesor itu guru besar, maha dosen, puncak intelektualitas tertinggi yang bisa didefinisikan manusia. Yang saya maksud profesor pada masa itu adalah scientist, ilmuwan, penemu, bukan guru besar. Saya selalu marah kalau ada yang bertanya,"Kenapa nggak jadi dokter aja?" "Nggak mauk, pokoknya mau jadi profesor!" ahahahaha. Dasar bocah sableng.
Seiring dengan makin bertambahnya usia dan dosis kedewasaan yang saya punya, bayangan masa depan untuk menjadi guru makin sering berlari-lari dalam pikiran saya. Guru itu pahalanya banyak. Diantara amal yang tidak akan terputus dan menjanjikan pahala yang terus mengalir adalah ilmu yang bermanfaat. Dan itu yang diberikan oleh seorang guru kepada muridnya. Saya sangat menikmati kegiatan mengajar, terutama jika melihat orang lain mengangguk-angguk paham atas penjelasan saya. Nah, ketika sampai di tahap orang yang saya ajari itu berkata,"Ooo.. .. gitu ya. Sip2. ngerti gue," Saya bisa sampai orgasme!
Tapi kalau dipikir2, kok ya kalau saya jadi guru, sepertinya kehidupan saya secara finansial kurang sejahtera, kurang secure. Apa ya, profesi yang di satu sisi orientasi utamanya memberi dan menyuplai sebanyak-banyaknya manfaat untuk orang lain, tapi di sisi lain menjamin kesejahteraan hidup untuk saya dan keluarga? Saya tidak kepingin jadi kaya, tapi cukup di level financially secure. Sepertinya, dokter adalah jawaban yang paling tepat. Jadi dokter itu belum tentu kaya, tapi insyaAllah tidak akan miskin, begitu kata salah satu senior saya di Fakultas Kedokteran.
Saya tidak pernah suka mengejar uang. Mungkin ini hasil didikan ayah saya yang selalu menekankan kesederhanaan dalam semua hal. Saya tidak suka jadi orang kaya, tapi saya tahu bahwa saya butuh untuk jadi orang kaya. Shodaqoh jariyah adalah pohon pahala, ladang amal yang merupakan previlege bagi orang-orang kaya. Agak sulit bagi orang yang tak punya duit untuk turut menyumbang pembangunan masjid, membangun sekolah, patungan mengaspal jalan umum, memberi tambahan modal usaha untuk industri kecil, dan berbagai peluang amal lain yang jelas-jelas membutuhkan uang.
Mohon maaf, saya tidak menemukan profesi lain di luar dokter dan guru yang visi misinya adalah memberi dan melayani. Maka dari itu, tidak heran jika masyarakat akan sangat marah ketika kesehatan dan pendidikan dikomersilkan, dibuat hitung2an ala pedagang atau pengusaha. Karena dalam kamus kebanyakan orang, dokter dan guru adalah profesi yang seharusnya tidak berpamrih, dan haram dibuat neraca laba-ruginya. Apesnya, ketika kesehatan serta pendidikan dijadikan bisnis, dokter dan guru adalah profesi yang paling menderita, karena menerima komplain paling banyak dari para customernya. Ketika biaya pendidikan mahal, pengelola institusi pendidikan dihujat. Ketika biaya kesehatan mahal, dokter dicaci maki, dicap komersil dan tidak ikhlas. Padahal, berapa sih gaji guru, dosen, dan pendapatan dokter?
Dalam mata rantai bisnis kesehatan dan pendidikan, dokter dan guru itu ada di rantai makanan terbawah, mirip tikus atau kodok. Predatornya adalah penerbit, kontraktor, dan pabrik farmasi. Ketika biaya pendidikan mahal, yang harus repot memikirkan pelanggan adalah dokter dan guru. Padahal kontributor biaya terbesar adalah masalah infrastruktur, bukan jasa, yang perannya dilakoni penerbit, kontraktor, pabrik farmasi dan teman2nya. Biaya beli obat jelas jauh lebih mahal daripada jasa dokter. Ongkos buku jauh lebih mahal daripada uang SPP. Dan uang pangkal sekolah yang biasanya untuk perbaikan gedung hampir tidak pernah tidak memberatkan siswa dan menjebol dompet orang tua.
Masyarakat kita jarang sekali menyoroti kenapa para penerbit tidak kunjung memberikan harga spesial untuk buku-buku sekolah. Pasien juga jarang mempertanyakan kenapa pabrik obat tidak punya niat untuk memproduksi obat murah secara istiqomah. Dan orang juga seringkali luput untuk menuntut para pemborong dan arsitek untuk tidak menggunakan hitung-hitungan konvensional ketika diminta membangun fasilitas pendidikan atau kesehatan. Kompensasinya, sebagai garda terdepan, dokter dan guru lah yang harus berperilaku sebagai customer service yang baik, menjelaskan, menentramkan, serta membantu mengelus dada masyarakat.
Kata salah seorang guru saya, masalahnya berpangkal di political will, perkara kemauan. Kalau will-nya sudah ada, how-nya akan mengikuti, dan way-nya akan langsung tampak jelas. Karena itu pemerintah punya peran yang sangat besar di sini.
Dalam primbon saya, penanganan masalah yang sudah kadung bersifat sistemik itu butuh solusi yang juga sistemik. Harus di bom dulu, baru masalah yang tersisa ditembaki satu per satu. Masing-masing punya peran sendiri, sesuai maqom dan derajatnya, baik yang ngebom, atau yang menembak. Pemerintah yang memang punya bom, harus berani ngebom. Dan para dokter dan guru yang punya senapan, silakan menembak. Kalau pemerintah ogah ngebom, saya mau jadi eksekutornya, jadi pelaku pemboman. Tapi sebelum sampai di tahap itu, saya masih harus banyak belajar untuk jadi penembak jitu. Banyak membaca, meminta pemeriksaan penunjang diagnostik yang sesuai keperluan, membuat resep yang rasional, dan tahu kapan harus segera merujuk.
Wallahua'lam.

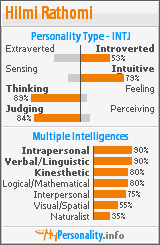

Tidak ada komentar:
Posting Komentar